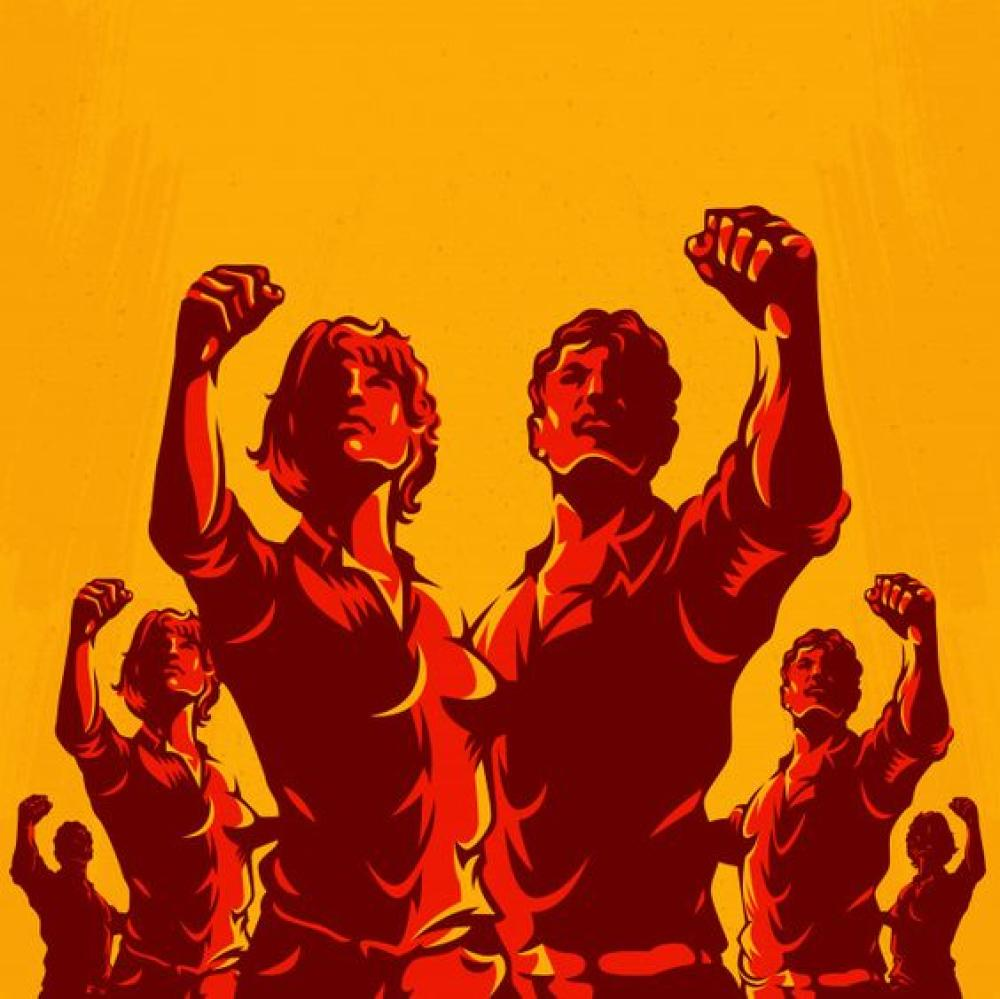Dalam ranah politik modern, dominasi kekuasaan tidak lagi semata-mata dibangun melalui kekuatan koersif atau transaksional. Seiring berkembangnya kesadaran masyarakat, lahir kebutuhan akan ikatan emosional dan simbolik antara rakyat dan pemimpin. Fenomena ini dikaji dengan tajam oleh Yoshinori Nishizaki dalam teorinya tentang identitas sosial positif (Social Identity Theory/SIT). Menurut Nishizaki, pemimpin dapat bertahan dan diterima luas bukan hanya karena kekuatan atau keuntungan materi yang dijanjikan, melainkan karena keberhasilannya membangun citra kolektif yang membanggakan.
Identitas sosial positif ini terbentuk melalui penciptaan simbol-simbol pembangunan—baik yang bersifat corporeal (fisik) seperti taman, jalan, sekolah, maupun incorporeal (non-fisik) seperti festival budaya, upacara keagamaan, atau aksi sosial. Simbol-simbol ini diperkuat melalui simbol iklan seperti baliho, media sosial, atau liputan media massa yang mencitrakan pemimpin sebagai figur keberhasilan, kepahlawanan dan perhatian.
Di Indonesia, terutama pasca-reformasi, fenomena ini terlihat nyata dalam politik lokal. Dominasi kekuasaan di banyak daerah tidak lagi ditopang hanya oleh politik uang, tetapi juga oleh narasi sosial kolektif yang mengikat rakyat dalam satu “cerita bersama” tentang kemajuan daerah mereka—sebuah cerita di mana pemimpin lokal menjadi tokoh utamanya atu role model.
Simbolisme Politik di Era Reformasi
Contoh paling menonjol adalah figure Ridwan Kamil saat menjabat Wali Kota Bandung (2013–2018). Ia tidak hanya membangun infrastruktur fisik seperti taman-taman tematik, jalur pedestrian, dan sistem kota pintar, tetapi juga meluncurkan festival budaya, gerakan cinta lingkungan, dan kampanye kreatif di media sosial. Ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi penciptaan identitas: warga Bandung diajak merasa bangga sebagai bagian dari “kota kreatif” yang berkelas dunia.
Sebenarnya apa yang dibangun Ridwan Kamil bukan sekadar taman, tetapi narasi tentang kemajuan—tentang Bandung yang modern, artistik, dan ramah bagi generasi muda. Ini membentuk identitas sosial positif yang memperkuat loyalitas publik pada pemimpinnya yang dilihat sebagai orang hebat. Politiknya ini lebih bernuansa emosional daripada transaksional.
Demikian pula tentang kisah serupa yang terjadi di Surabaya di bawah Tri Rismaharini. Melalui program taman kota, kampung-kampung warna-warni, pelayanan publik cepat tanggap, dan blusukan yang penuh empati, Risma menciptakan citra sebagai “ibu rakyat Surabaya”. Loyalitas masyarakat terhadap Risma dibangun bukan lewat patronase material, melainkan lewat kedekatan emosional dan simbol-simbol moralitas yang dirawat secara konsisten. Risma terlihat menjelma sebagai Hero bagi masyarakat Surabaya.
Kita bisa lihat contoh lain lagi yaitu sosok Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi. Ia membangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga memperkenalkan festival budaya berkelas internasional seperti Banyuwangi Ethno Carnival misalnya. Melalui karnaval ini, Banyuwangi diangkat dari citra daerah tertinggal menjadi simbol kebangkitan daerah pinggiran. Dia juga mengembangkan corak batik Banyuwangi dengan menggelar Fashion Show berkelas Internasional. Maka Warga Banyuwangi merasa memiliki cerita sukses kolektif, di mana Anas berperan sebagai katalisnya. Azwar Anas muncul sebagai pemimpin yang penuh perhatian dan kecintaan terhadap daerahnya.
Antara Simbolisme dan Politik Kosmetik
Akan tetapi ternyata tidak semua praktik simbolik berujung pada transformasi substantif. Dalam banyak kasus, simbol simbol itu justru direduksi menjadi sekedar alat kosmetik politik. Pemimpin membangun proyek mercusuar—seperti taman kota yang megah atau ikon wisata dadakan—sementara masalah dasar seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan tetap terabaikan.
Khusus dalam negara patrimonial seperti Indonesia, di mana hubungan patron-klien masih kuat, simbol-simbol kadang dibiayai dari sumber daya negara dan disebarluaskan melalui jaringan klientelistik. Maka loyalitas masyarakat dibentuk bukan dari perbaikan nyata, melainkan dari persepsi pencapaian yang direkayasa. Pembangunan taman tanpa perbaikan sanitasi, festival budaya tanpa pengentasan kemiskinan, dan blusukan penuh hura hura di layar kaca adalah merupakan contoh dari politik kosmetik yang berbahaya.
Harus dipahami bahwa fenomena pemimpin viral di media sosial, yang sering memamerkan aksi-aksi simpatik tanpa perubahan struktural nyata, juga bagian dari masalah ini. Politik menjadi pertunjukan atau panggung sandiwara, di mana substansi dikalahkan oleh gaya. Jargon yang berkembang adalah mengutamakan gaya dari pada mutu.
Tantangan dan Peluang
Akan tetapi, tidak salah juga, Identitas sosial positif tetap menawarkan peluang besar untuk memperkuat demokrasi, dengan catatan digunakan dengan etika dan orientasi pelayanan masyarakat. Pemimpin idealnya menggunakan simbol untuk mendorong partisipasi, mempererat solidaritas sosial, dan membangun kesadaran kritis rakyat—bukan sekadar mengejar popularitas.
Di dalam era di mana persepsi kerap mampu mengalahkan kenyataan, tugas publik dan media adalah mengkritisi apakah simbol-simbol itu berakar pada perubahan nyata atau hanya ilusi visual. Disinilah peran pendidikan politik warga, jurnalisme investigatif, dan keterbukaan data dapat menjadi kunci untuk menjaga agar politik simbolik tetap dapat terjaga berada di jalur demokrasi yang sehat.
Itu sebabnya kita perlu membangun politik yang tidak anti-simbol, melainkan mengisi simbol dengan penuh makna. Karena pada akhirnya, simbolisme yang beretika dan berbasis prestasi bisa dan mampu menjadi jembatan antara kekuasaan dan kepercayaan rakyat—sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam demokrasi Indonesia hari ini. Sesuatu yang sekarang tampak merajalela berkembang dengan luar biasa. Sesuatu yang mengaburkan makna dari nilai Demokrasi yang bernafaskan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.
Nyatanya Identitas Sosial Positif sudah muncul sebagai sebuah jalan baru dominasi politik di Indonesia. Mudah mudahan sebagai jalan baru menuju Indonesia yang lebih baik.
Jakarta 27 April 2025
Chappy Hakim – Pusat Studi Air Power Indonesia